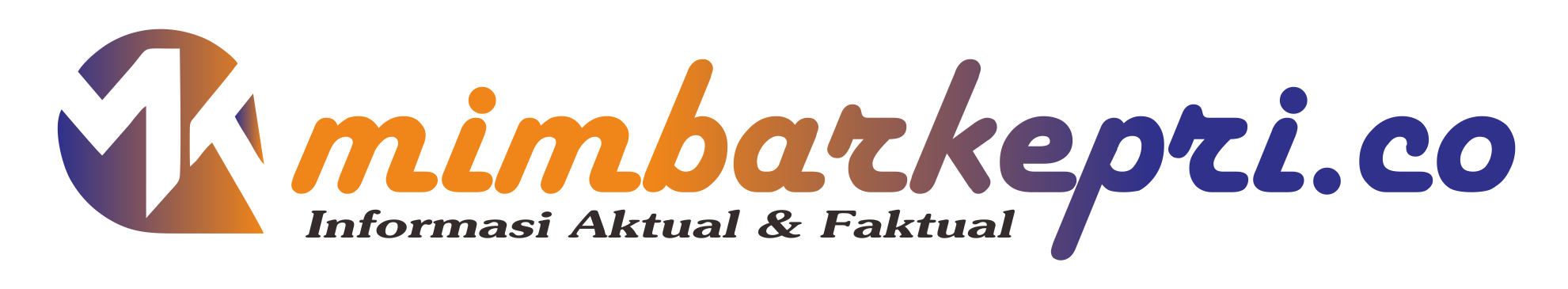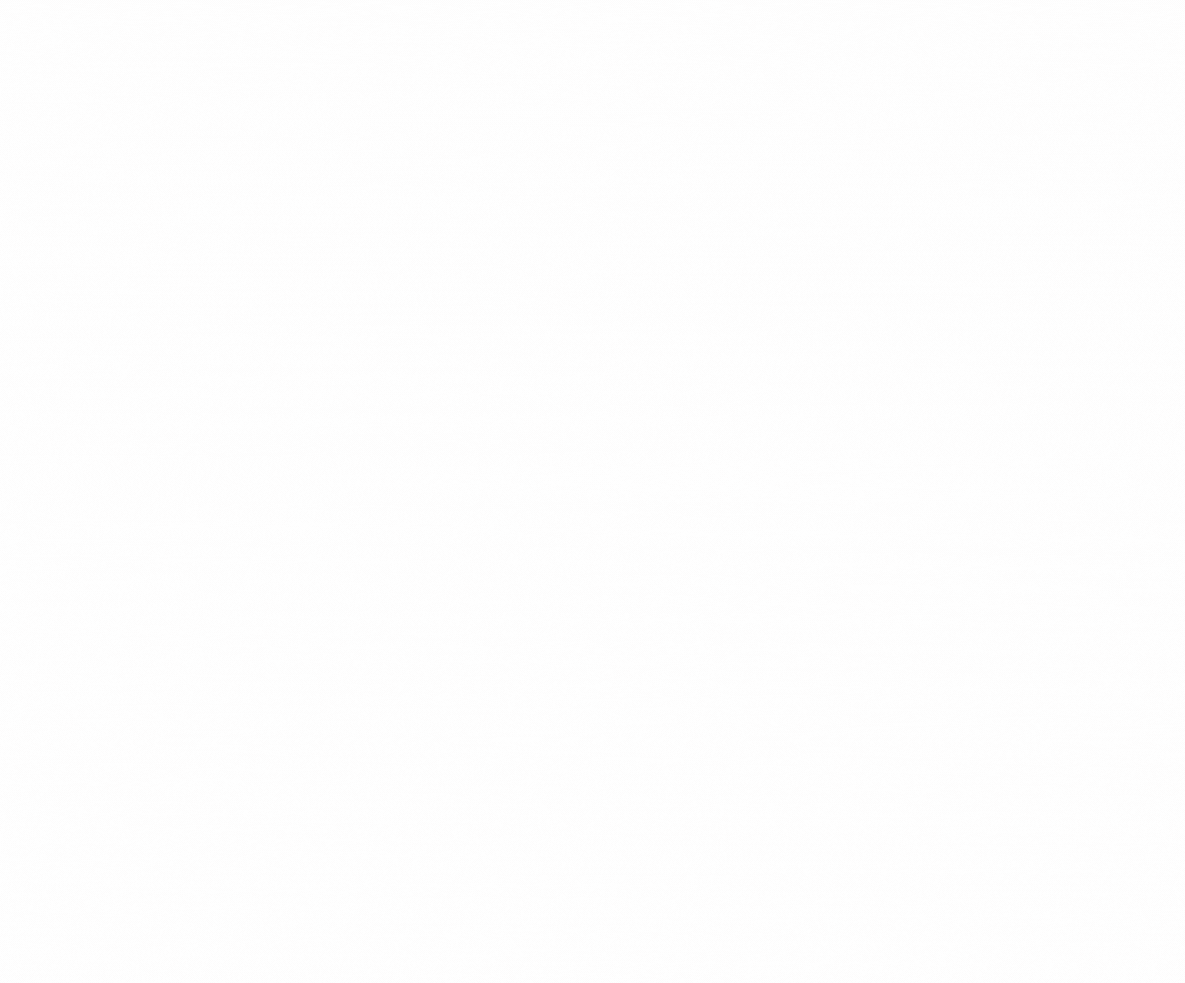SUTRADARA Guillermo del Toro kembali menunjukkan keahliannya dalam menghidupkan kisah klasik dengan cara yang elegan dan emosional. Melalui Frankenstein (2025), ia tidak sekadar mengadaptasi novel Mary Shelley, tetapi menyusun ulang narasinya menjadi pengalaman sinematik baru yang lebih intim, tragis, dan penuh simbolisme.
Frankenstein: Adaptasi yang Tidak Sepenuhnya Setia tetapi Bermakna
Kisah Frankenstein karya Mary Shelley dikenal sebagai horor gotik tentang penciptaan yang keliru dan konsekuensinya. Namun, di tangan del Toro, kisah itu berubah menjadi refleksi mendalam tentang kemanusiaan, trauma, dan siklus kekerasan.
Dalam novel, Victor Frankenstein tumbuh dengan keluarga penuh kasih: Ayah penyayang, adik dicintainya, serta kehidupan stabil. Namun dalam film, del Toro menggeser fokus tersebut. Narasinya lebih menyoroti kesepian Victor, menjadikannya bagian dari siklus kekerasan yang ia teruskan pada ciptaannya sendiri. Alih-alih menjadi “jenius yang ceroboh”, Victor digambarkan seperti seseorang yang membentuk monster bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional.
Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah bagaimana seluruh karakter dibangun dengan detail emosional, psikologis, dan moral.
Jacob Elordi sebagai The Creature
Jacob Elordi memberikan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya. Meski karakternya minim dialog, gesture dan gerak tubuhnya begitu lembut, rapuh, namun tetap anggun. Del Toro menggambarkan The Creature sebagai makhluk baru yang “baru lahir”, penuh kebingungan dan kerentanan. Elordi mengeksekusinya dengan pergerakan yang terkontrol dan lembut, ekspresi yang penuh rasa ingin tahu, dan bahasa tubuh yang menyerupai gabungan antara manusia dan sesuatu yang masih belajar menjadi manusia.
Awalnya, penonton disesatkan dengan tampilan The Creature sebagai sosok menakutkan dan brutal. Namun seiring cerita berjalan, terungkap bahwa Victor-lah yang sebenarnya menjadi antagonis; penuh ego, manipulatif, dan tega memperlakukan ciptaannya seperti objek dengan memanggilnya sebagai ‘it’.
Naskah, Metafora, dan Simbolisme yang Kuat
Meskipun alur cerita film ini tampak sederhana dan langsung pada intinya, naskahnya ternyata dipenuhi metafora subtil dan simbolisme yang memperkaya makna. Wardrobe dan makeup tidak dibuat semata-mata untuk estetika visual, melainkan menjadi bagian penting dari narasi. Mia Goth memerankan dua karakter: ibu Victor dan Elizabeth, kekasih Victor.
Pilihan ini bukan tanpa tujuan. Hubungan visual antara kedua karakter itu menegaskan obsesi Victor terhadap figur ibunya. Bahkan peti jenazah sang ibu dirancang menyerupai gaun yang kelak dipakai Elizabeth, memperkuat gagasan bahwa perempuan yang ia cintai hanyalah cerminan sosok ibu yang tak pernah bisa ia lepaskan. Ini adalah simbolisme psikologis yang gelap, namun dieksekusi dengan keanggunan artistik khas del Toro.
Setiap Frame seperti Lukisan
Secara visual, Frankenstein adalah mahakarya. Del Toro menghidupkan atmosfer gothic abad ke-19 (sekitar era 1810–1820-an, yang memang menjadi latar asli karya Shelley) dengan detail yang memukau. Sinematografinya menyuguhkan nuansa kelam namun elegan, kaya tekstur, dan penuh kedalaman. Color grading yang dramatis, mise-en-scène yang terencana dengan matang, serta komposisi kamera yang indah membuat setiap frame terlihat seperti lukisan klasik. Elemen-elemen visual ini bukan hanya memperkuat suasana, tetapi menjadi bahasa emosional tersendiri yang menggambarkan kesendirian, kehilangan, dan tragedi yang dialami para karakter.
Frankenstein (2025) adalah adaptasi yang tidak berusaha meniru novel Mary Shelley secara literal, tetapi justru menggali inti moral dan emosional dari kisah tersebut. Guillermo del Toro menciptakan film yang indah, menyayat, dan penuh filosofi. Film ini kini dapat ditonton di streaming platform Netflix.